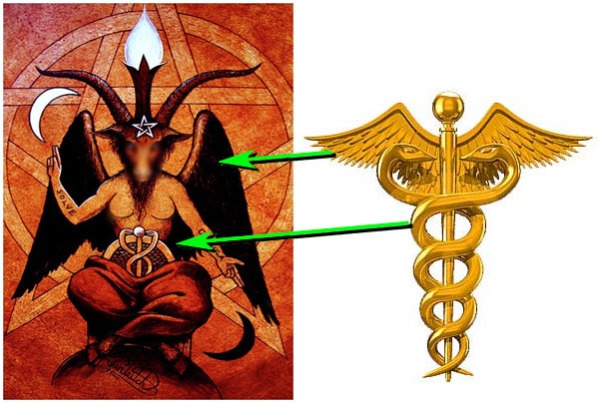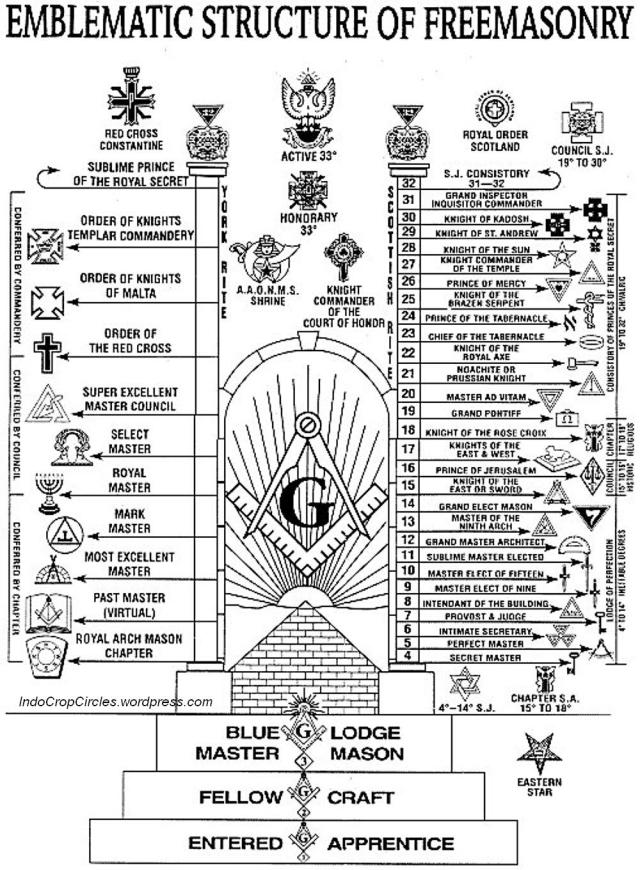Selain ajaran Theosofi yang merusak akidah Islam, para aktivis Theosofi di Indonesia pada masa lalu banyak terlibat dalam berbagai aksi pelecehan terhadap ajaran Islam. Ironisnya, mereka adalah orang-orang yang disebut dalam buku-buku sejarah sebagai tokoh-tokoh nasional.
Dalam buku “Sejarah Indonesia Modern”, sejarawan MC Ricklef menyatakan, Theosofi di Indonesia pada masa lalu banyak terlibat dalam berbagai aksi pelecehan terhadap Islam.
Bukan hanya ajarannya yang banyak berseberangan dengan akidah Islam
sebagaimana banyak dipaparkan oleh penulis pada tulisan beberapa edisi
lalu, namun juga para aktivis Theosofi yang merupakan elit-elit nasional
pada masa lalu, juga banyak melakukan pelecehan terhadap Islam. Para
aktivis Theosofi yang umumnya elit Jawa penganut kebatinan, menganggap
Islam sebagai agama impor yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan jati
diri bangsa Jawa.
A.D El Marzededeq, peneliti jaringan Freemason di Indonesia dan penulis buku “Freemasonry Yahudi Melanda Dunia Islam”
menyatakan tentang gambaran elit Jawa dalam kelompok Theosofi dan
Freemasonry pada masa lalu. Marzededeq menulis, “Perkumpulan kebatinan
di Jawa yang berpangkal dari paham Syekh Siti Jenar makin mendukung
keberadaan Vrijmetselarij (Freemason). Para elit Jawa yang menganut
paham wihdatul wujud (menyatunya manusia dengan Tuhan, red) yang dibawa
oleh Syekh Siti Jenar, kemudian banyak yang menjadi anggota
Theosofi-Freemasonry, baik secara murni ataupun mencampuradukkannya
dengan kebatinan Jawa…” (hal.8)
Para elit Jawa dan tokoh-tokoh kebangsaan
yang tergabung sebagai anggota Theosofi-Freemason di Indonesia pada
masa lalu kerap kali berada di balik berbagai pelecehan terhadap Islam.
Misalnya, mereka menyebut ke Boven Digul lebih baik daripada ke Makkah,
mencela syari’at poligami, dan menyebut agama Jawa (Gomojowo) atau
Kejawen lebih baik daripada Islam. Penghinaan-penghinaan tersebut
dilakukan secara sadar melalui tulisan-tulisan di media massa dan
ceramah-ceramah di perkumpulan mereka. Penghinaan-penghinaan itu makin
meruncing, ketika para anggota Theosofi-Freemason yang aktif dalam
organisasi Boedi Oetomo, berseteru dengan aktivis Sarekat Islam.
Pada sebuah rapat Gubernemen Boemipoetra
tahun 1913, Radjiman Wediodiningrat, anggota Theosofi-Freemason,
menyampaikan pidato berjudul “Een Studie Omtrent de S.I (Sebuah Studi
tentang Sarekat Islam)” yang menghina anggota SI sebagai orang rendahan,
kurang berpendidikan, dan mengedepankan emosional dengan bergabung
dalam organisasi Sarekat Islam. Radjiman dengan bangga mengatakan, bakat
dan kemampuan orang Jawa yang ada pada para aktivis Boedi Oetomo lebih
unggul ketimbang ajaran Islam yang dianut oleh para aktivis Sarekat
Islam. Pada kongres Boedi Oetomo tahun 1917, ketika umat Islam yang
aktif di Boedi Oetomo meminta agar organisasi ini memperhatikan aspirasi
umat Islam, Radjiman dengan tegas menolaknya. Radjiman mengatakan,
“Sama sekali tidak bisa dipastikan bahwa orang Jawa di Jawa Tengah
sungguh-sungguh dan sepenuhnya menganut agama Islam.”
Anggota Theosofi lainnya yang juga
aktivis Boedi Oetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, juga melontarkan
pernyataan yang melecehkan Islam. Adik dari dr. Tjipto Mangoekoesomo ini
mengatakan, “Dalam banyak hal, agama Islam bahkan kurang akrab dan
kurang ramah hingga sering nampak bermusuhan dengan tabiat kebiasaan
kita. Pertama-tama ini terbukti dari larangan untuk menyalin Qur’an ke
dalam bahasa Jawa. Rakyat Jawa biasa sekali mungkin memandang itu biasa.
Tetapi seorang nasionalis yang berpikir, merasakan hal itu sebagai
hinaan yang sangat rendah. Apakah bahasa kita yang indah itu kurang
patut, terlalu profan untuk menyampaikan pesan Nabi?”
Goenawan Mangoenkoesomo adalah diantara
tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan di Loji Theosofi Belanda pada
1918, selain Ki Hadjar Dewantara, dalam rangka memperingati 10 tahun
berdirinya Boedi Oetomo. Apa yang ditulis Goenawan di atas dikutip dari
buku Soembangsih Gedenkboek Boedi Oetomo 1908-Mei 1918 yang diterbitkan
di Amsterdam, Belanda. Dalam buku yang sama, masih dengan nada
melecehkan, Goenawan menulis, “Jika kita berlutut dan bersembahyang,
maka bahasa yang boleh dipakai adalah bahasanya bangsa Arab…”
Organisasi kepemudaan yang bercorak
kebatinan Jawa pada masa lalu juga tak lepas dari pengaruh
Theosofi-Freemason. Sejarah mencatat, organisasi kepemudaan ini disusupi
kepentingan yang berusaha menyingkirkan Islam.
Dalam catatan sejarah, keluarnya
Syamsuridjal dari keanggotaan Jong Java (Perkumpulan Pemuda Jawa) dan
kemudian mendirikan Jong Islamietend Bond (JIB/ Perhimpunan Pemuda
Islam) adalah karena organisasi Jong Java menolak untuk mengadakan
kuliah atau pengajaran keislaman bagi anggotanya yang beragama Islam
dalam organisasi ini. Sementara, agama Katolik dan Theosofi justru
mendapat tempat untuk diajarkan dalam pertemuan-pertemuan Jong Java.
Pada masa lalu, Jong Java adalah organisasi yang berada dalam pengaruh
kebatinan Theosofi.
Sosok yang dianggap berpengaruh dalam
menyingkirkan Islam dari organisasi Jong Java adalah Hendrik Kraemer,
utusan Perkumpulan Bibel Belanda yang diangkat menjadi penasihat Jong
Java. Sejarawan Karel Steenbrink dalam “Kawan dalam Pertikaian:Kaum
Kolonial Belanda Islam di Indonesia 1596-1942″ menulis bahwa Kraemer
adalah misionaris Ordo Jesuit yang aktif memberikan kuliah Theosofi dan
ajaran Katolik kepada anggota Jong Java. Di organisasi pemuda inilah,
Kraemer masuk untuk menihilkan ajaran-ajaran Islam. (Lihat, Karel Steenbrink, hal.162-163)
Selain Syamsuridjal, permintaan agar
Islam diajarkan dalam pengajaran di Jong Java juga disuarakan Kasman
Singodimedjo. Kasman bahkan mengusulkan agar Jong Java menggunakan asas
Islam dalam pergerakan dan menjadi pionir bagi organisasi-organisasi
pemuda lain, seperti Jong Sumatrenan, Jong Celebes, dan Pemuda Kaum
Betawi. Kasman beralasan, Islam adalah agama mayoritas di Nusantara, dan
mampu menyelesaikan segala sengketa dalam organisasi-organisasi yang
saat itu banyak terpecah belah. Karena tak disetujui, maka pada 1
Januari 1925, para pemuda Islam mendirikan Jong Islamietend Bond
(JIB/Perkumpulan Pemuda Islam) di Jakarta. Dengan menggunakan kata
“Islam”, JIB jelas ingin menghapus sekat-sekat kedaerahan dan kesukuan,
dan mengikat dalam tali Islam.
Dalam statuten JIB dijelaskan tentang
asas dan tujuan perkumpulan ini: Pertama, mempelajari agama Islam dan
menganjurkan agar ajaran-ajarannya diamalkan. Kedua, menumbuhkan simpati
terhadap Islam dan pengikutnya, disamping toleransi yang positif
terhadap orang-orang yang berlainan agama. Dalam kongres pertama JIB,
Syamsuridjal dengan tegas menyatakan, “Berjuang untuk Islam, itulah jiwa
organisasi kita.”
Untuk mengkonter pelecehan-pelecehan
terhadap Islam, para pemuda Islam yang tergabung dalam JIB kemudian
mendirikan Majalah Het Licht yang berarti Cahaya (An-Nur). Majalah ini
dengan tegas memposisikan dirinya sebagai media yang berusaha menangkal
upaya dari kelompok di luar Islam yang ingin memadamkan Cahaya Allah,
sebagaimana yang pernah mereka rasakan saat masih berada di Jong Java. Motto
Majalah Het Licht yang tercantum dalam sampul depan majalah ini dengan
tegas merujuk pada Surah At-Taubah ayat 32: “Mereka berusaha memadamkan
cahaya (agama) Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menolaknya,
malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir
itu tidak menyukai.”
JIB dengan tegas juga mengkonter pelecehan terhadap Islam, sebagaimana dilakukan oleh Majalah Bangoen, majalah yang dipimpin oleh aktifis Theosofi, Siti Soemandari. Majalah Bangoen yang dibiayai oleh organisasi Freemason pada edisi 9-10 tahun 1937 memuat artikel-artikel yang menghina istri-istri Rasulullah. Penghinaan itu kemudian disambut oleh para aktivis JIB dan umat Islam lainnya dengan menggelar rapat akbar di Batavia.
JIB dengan tegas juga mengkonter pelecehan terhadap Islam, sebagaimana dilakukan oleh Majalah Bangoen, majalah yang dipimpin oleh aktifis Theosofi, Siti Soemandari. Majalah Bangoen yang dibiayai oleh organisasi Freemason pada edisi 9-10 tahun 1937 memuat artikel-artikel yang menghina istri-istri Rasulullah. Penghinaan itu kemudian disambut oleh para aktivis JIB dan umat Islam lainnya dengan menggelar rapat akbar di Batavia.
Sebelumnya, pada 1926, dua tahun sebelum
peristiwa Sumpah Pemuda, para aktivis muda yang berasal dari Jong
Theosofen (Pemuda Theosofi) dan Jong Vrijmetselaarij (Pemuda Freemason)
sibuk mengadakan pertemuan-pertemuan kepemudaan. Pada tahun yang sama,
mereka berusaha mengadakan kongres pemuda di Batavia yang ditolak oleh
JIB, karena kongres ini didanai oleh organisasi Freemason dan diadakan
di Loge Broderketen, Batavia. Alasan penolakan JIB, dikhawatirkan
kongres ini disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang berusaha
menyingkirkan Islam. Apalagi, Tabrani, penggagas kongres ini adalah
anggota Freemason dan pernah mendapat beasiswa dari Dienaren van Indie
(Abdi Hindia), sebuah lembaga beasiswa yang dikelola aktivis
Theosofi-Freemason.
Pada tahun 1922, sebagaimana ditulis oleh
A.D El Marzededeq dalam “Jaringan Gelap Freemasonry: Sejarah dan
Perkembangannya Hingga ke Indonesia” disebutkan bahwa di Loge
Broderketen, Batavia, juga pernah terjadi aksi pelecehan terhadap Islam
oleh salah seorang aktivis Freemason yang memberikan pidato pada saat
itu dengan mengatakan, “Islam menurut mereka itu merupakan paduan kultur
Arab, Yudaisme, dan Kristen. Indonesia mempunyai kultur sendiri, dan
kultur Arab tidak lebih tinggi dari Indonesia. Mana mereka mempunyai
Borobudur dan Mendut?
Para aktivis nasionalis sekular, terutama
mereka yang aktif dalam organisasi Theosofi dan Freemason berusaha
menjauhkan peran agama, khususnya Islam, dalam sistem pemerintahan.
Negara tak perlu diatur oleh agama, cukup dengan nalar dan moral
manusia.
Paham kebangsaan yang diusung oleh
kelompok nasionalis sekular pada masa lalu di negeri ini adalah ideologi
“keramat” yang netral agama (laa diniyah) dan kerap
dibentur-benturkan dengan Islam. Kelompok nasionalis sekular,
sebagaimana tercermin dalam pemikiran Soekarno dan para aktivis
kebangsaan lainnya yang ada dalam organisasi seperti Boedi Oetomo,
adalah mereka yang menolak agama turut campur dalam sistem pemeritahan.
Mereka berusaha menjauhkan peran agama, khususnya Islam, dalam sistem
berbangsa dan bernegara. Mereka menjadikan Turki sekular di bawah
pimpinan Mustafa Kemal At-Taturk sebagai kiblat dalam mengelola
pemerintahan.
Kiblat kelompok kebangsaan kepada Turki
Sekular tercermin jelas dalam pernyataan tokoh Boedi Oetomo, dr Soetomo
yang mengatakan, “Perkembangan yang terjadi di Turki adalah petunjuk
jelas, bahwa cita-cita “Pan-Islamisme” telah digantikan oleh
nasionalisme.” Dengan rasa bangga, saat berpidato dalam Kongres Partai
Indonesia Raya (Parindra) pada 1937, Soetomo mengatakan,”Kita harus
mengambil contoh dari bangsa-bangsa Jahudi, jang menghidupkan kembali
bahasa Ibrani. Sedang bangsa Turki dan Tsjech kembali menghormati
bangsanya sendiri.”
Tokoh Boedi Oetomo lainnya, dr Tjipto
Mangoenkoesomo, juga dengan sinis meminta agar bangsa ini mewaspadai
bahaya “Pan-Islamisme”, yaitu bahaya persatuan Islam yang membentang di
berbagai belahan dunia, dengan sistem dan pemerintahan Islam di bawah
khilafah Islamiyah. Pada 1928, Tjipto Mangoenkoesoemo menulis surat
kepada Soekarno yang isinya mengingatkan kaum muda untuk berhati-hati
akan bahaya Pan-Islamisme yang menjadi agenda tersembunyi Haji Agus
Salim dan HOS Tjokroaminoto. Tjipto khawatir, para aktivis Islam yang
dituduh memiliki agenda mengobarkan Pan-Islamisme di Nusantara itu bisa
menguasai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jika mereka
berhasil masuk dalam PPKI, kata Tjipto, maka cita-cita kebangsaan akan
hancur.
Pernyataan Tjipto Mangoenkoesomo makin
memperjelas sikap kalangan pengusung paham kebangsaan atau nasionalis
sekular yang berusaha membendung segala upaya dan cita-cita Islam dalam
pergerakan nasional dan pemerintahan di negeri ini. Sebelum kemerdekaan,
perdebatan soal Islam dan kebangsaan antara kelompok nasionalis sekular
yang diwakili oleh Soekarno dan kawan-kawan dengan kelompok Islam yang
diwakili A. Hassan, M. Natsir, dan H. Agus Salim begitu menguat ke
publik. Berbagai polemik tentang dasar negara menjadi perbincangan
terbuka di media massa. Kelompok Islam menginginkan negara yang nantinya
merdeka, menjadikan Islam sebagai landasan bernegara. Sementara
kelompok nasionalis sekular berusaha memisahkan agama dan pemerintahan.
“Manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat-masyarakat manusia,
ia selalu dipakai sebagai alat penghukum di tangan raja-raja,
orang-orang zalim, dan orang-orang tangan besi,” kata Soekarno mengutip
perkataan Mahmud Essad Bey.
Sarekat Islam (SI), sebagai organisasi
pergerakan yang mengusung cita-cita Islam, melalui tokohnya HOS
Tjokroaminoto memang menyerukan kepada SI untuk melancarkan gerakan tandzim guna
mengatur kehidupan rakyat di lapangan ekonomi, sosial, budaya, menurut
asas-asas Islam. Sedangkan H. Agus Salim, selain menyerukan perlawanan
terhadap kapitalisme, juga menyerukan tentang kekhilafahan Islam dan
Pan-Islamisme, sehingga berdiri apa yang disebut dengan Central Comite Chilafat. Nasionalisme dalam pengertian Salim adalah memajukan nusa dan bangsa berdasarkan cita-cita Islam.
Mohammad Natsir dalam Majalah Pembela Islam tahun 1931 menulis bahwa kelompok yang ingin memisahkan agama dari urusan negara adalah kelompok ”laa diniyah” (netral
agama). Natsir menegaskan, ada perbedaan cita-cita antara kelompok
kebangsaan dan para aktivis Islam tentang visi negara merdeka. Natsir
menyatakan, kemerdekaan bagi umat Islam adalah untuk kemerdekaan Islam,
supaya berlaku peraturan dan undang-undang Islam, untuk keselamatan dan
keutamaan umat Islam khususnya, dan untuk semua makhluk Allah umumnya.
Natsir menyindir kelompok nasionalis sekular dengan mengatakan,
“Pergerakan yang berdasarkan kebangsaan tidak akan ambil pusing, apakah
penduduk muslimin Indonesia yang banyaknya kurang lebih 85% dari
penduduk yang ada, menjadi murtad, bertukar agama. Kristen boleh,
Theosofi bagus, Budha masa bodoh.”
Sementara kelompok kebangsaan, terutama
mereka yang aktif dalam organisasi Theosofi dan Freemason,
mengampanyekan bahwa nasionalisme yang dibangun di negeri ini harus
sesuai dengan doktrin humanisme, di mana manusia berhak menentukan hukum
buatan sendiri yang bertujuan untuk mengabdi kepada kemanusiaan, tanpa
campur tangan agama manapun. Van Mook, tokoh Freemason di Hindia Belanda
ketika itu, dalam sebuah pidato di Loge Mataram, Yogyakarta, tahun
1924, mengatakan, “Freemasonry membimbing nasionalisme menuju cita-cita
luhur dari humanitas.”
Paham humanisme yang dibawa oleh
elit-elit kolonial, teruatama mereka yang aktif sebagai anggota Theosofi
dan Freemason inilah yang kemudian “ditularkan” kepada “anak-anak
didik” para priyai dan elit Jawa yang menjadi abdi kompeni. Mereka
mengampanyekan soal kesamaan semua agama-agama, tidak percaya dengan
hukum Tuhan dan mempercayai kodrat alam, dan tentu saja sebagaimana
trend imperialisme negara-negara Eropa ketika itu, adalah mengampanyekan
bahaya “Pan-Islamisme”, semangat solidaritas Islam dunia untuk
membangun sebuah pemerintahan.
Karena itu, untuk membendung
Pan-Islamisme di Nusantara, apalagi ketika itu banyak tokoh-tokoh Islam
yang pulang dari haji dan menimba ilmu di Makkah juga menyuarakan
Pan-Islamisme, maka pemerintah kolonial membentuk basis-basis tandingan
dengan mendukung berdirinya organisasi-organisasi kebangsaan seperti
Boedi Oetomo, Jong Java, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga
merangkul para priyai sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial,
memberi keluasan bagi anak-anak keturunan mereka untuk bersekolah di
negeri Belanda, dan mendirikan pendidikan-pendidikan netral (neutrale onderwijs), yang berbasis pada pembentukan karakter manusia dengan berpedoman pada hukum kodrat alam.
Tak sedikit dari para elit dan priyai
Jawa ketika itu, baik yang aktif dalam organisasi kebangsaan ataupun
mereka yang menjabat sebagai residen, asisten residen, wedana, dan
sebagainya yang masuk dalam organisasi Theosofi dan Freemason. Bahkan,
tak sedikit juga dari mereka yang masuk sebagai anggota Rotary Club,
sebuah lembaga kemanusiaan yang dibentuk oleh Zionisme Internasional.
Pelecehan demi pelecehan terhadap Islam dilakukan oleh para pengusung
kebangsaan, seperti pernyataan bahwa ke Boven Digul lebih baik daripada
ke Makkah, pergi haji adalah upaya menimbun modal nasional untuk
kepentingan asing, Islam adalah agama impor yang berusaha menjajah tanah
Jawa, dan sebagainya.
Theosofi-Freemason tidak mempercayai adanya ritual doa kepada Sang Maha Pencipta. Mereka juga tak mempercayai adanya surga dan neraka. Anggota Theosofi yang mengaku muslim, membuat penafsiran ajaran Islam dengan pemahaman yang menyimpang.
 Sebagai
perkumpulan kebatinan yang meyakini bahwa Tuhan punya banyak nama, dan
masing-masing agama hanyalah berbeda dalam memberi nama pada tuhannya,
maka penganut Theosofi yang mengaku beragama Islam, menerjemahkan
kalimat thayyibah “Laa Ilaaha Illallah” dengan “Tiada Gusti
Allah, melainkan Gusti Allah”. Terjemah tersebut kemudian dijelaskan,
bahwa pengertiannya ada dua macam: Pertama, kita tidak boleh percaya
lain rupa kekuasaan atau lain kekuatan melainkan Gusti Allah punya
kekuasaan sendiri. Kedua, yaitu yang Gusti Allah menempati badannya
manusia. Keterangan mengenai ini ditulis dalam Majalah Pewarta Theosofi Boeat Tanah Hindia Nederland, 1906.
Sebagai
perkumpulan kebatinan yang meyakini bahwa Tuhan punya banyak nama, dan
masing-masing agama hanyalah berbeda dalam memberi nama pada tuhannya,
maka penganut Theosofi yang mengaku beragama Islam, menerjemahkan
kalimat thayyibah “Laa Ilaaha Illallah” dengan “Tiada Gusti
Allah, melainkan Gusti Allah”. Terjemah tersebut kemudian dijelaskan,
bahwa pengertiannya ada dua macam: Pertama, kita tidak boleh percaya
lain rupa kekuasaan atau lain kekuatan melainkan Gusti Allah punya
kekuasaan sendiri. Kedua, yaitu yang Gusti Allah menempati badannya
manusia. Keterangan mengenai ini ditulis dalam Majalah Pewarta Theosofi Boeat Tanah Hindia Nederland, 1906.
Makna pertama, meskipun seolah terlihat
bagus, bahwa kita tidak boleh percaya kepada kekuasaan dan kekuatan
selain yang dipunya Gusti Allah, namun Gusti Allah dalam pandangan
Theosofi adalah Tuhan yang dimiliki oleh setiap agama-agama, yang
merupakan kesatuan batin dalam keyakinan (esoteris). Tuhan dalam
keyakinan Theosofi punya banyak nama: God, Yahweh, Sang Hyang, dan
lain-lain, yang pada hakikatnya menurut mereka merujuk pada Zat Yang
Satu, meskipun namanya berbeda-beda, meskipun agamanya berlainan rupa.
Tokoh sekular pendiri Yayasan Paramadina, Nurcholish Madjid pernah
membuat sebuah tulisan dengan judul “Satu Tuhan Banyak Jalan”.
Terjemahan menyimpang tentang kalimat “Laa Ilaaha Illallah” juga pernah dilakukan oleh mendiang Nurcholish Madjid. Ia menerjemahkan kalimat ”Laa Ilaaha Illallah” dengan
“Tiada tuhan melainkan Tuhan”. Cak Nur yang merupakan lokomotif gerakan
sekular di Indonesia ini membagi tuhan (dengan “t” kecil) dengan Tuhan
(dengan “T” besar). Terjemahan Cak Nur dianggap mengacu pada terjemahan
ala Barat dan Bibel, yang menyebut Tuhan dengan sebutan “god” (dengan
“g” kecil) dan “God” (dengan “G” besar). Dalam Kitab Mazmur 109:1, 2
disebutkan “Tuhan telah bersabda kepada tuhanku.”
Dalam Islam, kata “Allah” adalah lafzhul jalalah (lafazh yang tinggi dan mulia), yang disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 2679 kali, yang semuanya dalam bentuk singular (mufrad) atau tunggal. Allah dalam keyakinan Islam adalah “al-ma’bud bi haqqin”, Zat
satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang tidak ada bandingan-Nya,
tidak ada yang menyerupai-Nya, tidak berbilang dan tidak memiliki
nama-nama lain, kecuali Al-Asma’ Al-Husna yang merupakan
sifat-sifat keagungan-Nya. Kata “Allah” tidak bisa diartikan dengan
“Tuhan” sebagaimana kata “al-ilah”. (Lihat, Ahmad Husnan, Jangan
Terjemahkan Al-Qur’an Menurut Visi Injil dan Orientalis, Jakarta: Media
Dakwah, 1987)
Makna kedua dari kalimat “Laa Ilaaha Illallah” ala terjemah Theosofi, yaitu yang Gusti Allah menempati badannya manusia, adalah keyakinan kufur yang mengacu pada paham wihdatul wujud atau al-hulul. Paham ini pada masa lalu dikenal di Nusantara dengan istilah ”manunggaling kawula gusti”, yaitu
keyakinan bahwa manusia dan Tuhan itu manunggal, sebagaimana keyakinan
yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Theosofi
menyebut manunggalnya manusia dengan Tuhan sebagai pancaran yang disebut
dengan istilah “pletik Ilahi (God in being)”.
Manusia sejati (ingsun sejati) dalam
keyakinan Theosofi adalah manusia yang mengamalkan lelaku batin
sehingga bisa manunggal dengan Tuhan. Manusia sejati adalah pancaran
dari gambaran Tuhan. Maka Manusia Sejati harus mengamalkan asas-asas
Ilahi, yaitu kasih sayang, kebenaran, dan kesatuan hidup. “Dengan
mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal Tuhan, Kasunyatan Hidup,
Kebenaran. Tuhan itu Hidup, Jalan, Kebenaran, Kasih. Allah kasih
meliputi segala-galanya. Allah adalah semua dalam semua. Kita Hidup,
bergerak, dan ada di dalam Dia. “ Inilah yang disebut dengan pletik ilahi atau God in being. (PB Perwathin, No. 5, Tahun VIII, Mei 1973). Sang Kasih, menurut Theosofi, menggabungkan semua dalam kesatuan.
Keyakinan soal manunggalnya hamba dengan
Tuhan juga diungkapkan tokoh Boedi Oetomo, dokter Soetomo. Dalam buku
“Kenang-kenangan Dokter Soetomo” yang dihimpun oleh Paul W van der Veur,
disebutkan bahwa Soetomo pernah mengatakan bahwa pemancaran zat
Tuhan,”Itulah sebenarnya keyakinan saya. Itulah keyakinan yang mengalir
bersama darah dalam segala urat tubuh saya. Sungguh, sesuai-sesuai
benar.” (hal. 30). Soetomo juga mengatakan, “Aku dan Dia satu dalam
hakikat, yakni penjelmaan Tuhan. Aku penjelmaan Tuhan yang sadar…” (hal.31).
Soetomo sebagaimana para penganut
kebatinan Theosofi lainnya, tidak melakukan shalat lima waktu selayaknya
umat Islam lainnya, melainkan melakukan semedi, meditasi, yoga, dan
sebagainya. “Soetomo lebih mementingkan “semedi” untuk mendapat
ketenangan hidup, ketimbang sembahyang,” tulis Paul W van der Veur
(hal.31). Karena cukup hanya dengan semedi, maka para penganut kebatinan
juga tidak melakukan ritual doa kepada Sang Maha Kuasa. Bagi mereka
semedi yang melahirkan sikap eling sudah cukup untuk mendekatkan diri
pada Tuhan.
 Pendiri
Theosofi, Helena Petrovna Blavatsky dalam bukunya “Kunci Pembuka Ilmu
Theosofi (The Key to Theosophy)” menyatakan bahwa Theosofi tidak percaya
dengan doa, dan tidak melakukan doa. Theosofi mempercayai “doa kemauan”
yang ditujukan kepada Bapak di sorga dalam artian esoteris, yaitu Tuhan
yang tidak ada sangkut pautnya dengan bayangan manusia, atau Tuhan yang
menjadi intisari ilahiah yang dimiliki semua agama. Berdoa, kata
Blavatsky mengandung dua unsur negatif: Pertama, membunuh sifat percaya
diri manusia yang ada dalam diri manusia sendiri. Kedua, mengembangkan
sifat mementingkan diri sendiri. (hal.50).
Pendiri
Theosofi, Helena Petrovna Blavatsky dalam bukunya “Kunci Pembuka Ilmu
Theosofi (The Key to Theosophy)” menyatakan bahwa Theosofi tidak percaya
dengan doa, dan tidak melakukan doa. Theosofi mempercayai “doa kemauan”
yang ditujukan kepada Bapak di sorga dalam artian esoteris, yaitu Tuhan
yang tidak ada sangkut pautnya dengan bayangan manusia, atau Tuhan yang
menjadi intisari ilahiah yang dimiliki semua agama. Berdoa, kata
Blavatsky mengandung dua unsur negatif: Pertama, membunuh sifat percaya
diri manusia yang ada dalam diri manusia sendiri. Kedua, mengembangkan
sifat mementingkan diri sendiri. (hal.50).
Dalam Islam tentu berbeda, umat Islam
dianjurkan untuk berdoa sebagai sarana memohon pertolongan, memohon
perlindungan, mengadukan segala persoalan kepada Allah, Rabbul alamin.
Berdoa juga wujud dari sikap rendah hati seorang hamba dengan Tuhannya,
selain juga sarana untuk berkomunikasi secara intim dengan Sang Maha
Pencipta.“Memohonlah kepada-Ku, maka niscaya Aku akan kabulkan permohonanmu…” (QS. Ghafir: 60). Di ayat lain, Allah berfirman,“Hai
orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al Baqarah [2]: 153)
Selain tidak menjalankan ritual doa,
Theosofi-Freemason juga tidak meyakini adanya dosa dan pahala, surga dan
neraka, bahkan tidak mengakui adanya hukum Tuhan. Mereka berkeyakinan
adanya hukum “kodrat alam”, di mana ganjaran kebaikan dan hukuman bagi
kejahatan ditentukan oleh kodrat alam dan hati nurani. Keyakinan
Theosofi menyatakan, “Kalau Anda berbuat, maka akan ada orang yang
membalas berbuat baik. Kalau Anda berbuat jahat, maka akan ada orang
yang membalas kejahatan Anda. That’s all, ini saja.” Inilah yang disebut
dengan “kodrat alam.”
Keyakinan ini tentu bertolak belakang
dengan apa yang diajarkan Islam. Dalam Islam, orang yang berbuat baik,
selain dapat balasan dari manusia di dunia, juga akan mendapat balasan
pahala dari Allah di akhirat kelak. Begitu juga, jika berbuat jahat,
selain mendapat balasan kejahatan di dunia, juga akan mendapatkan dosa
di akhirat. Orang Islam yang beriman dan beramal shaleh akan masuk
surga, orang-orang yang mengaku Islam namun berbuat kejahatan dan
kemusyrikan, apalagi mereka yang di luar Islam atau kafir maka akan
mendapatkan balasan di neraka. Inilah hukum Tuhan, karena Islam meyakini
ada kehidupan lagi setelah kematian nanti.
[Sumber]